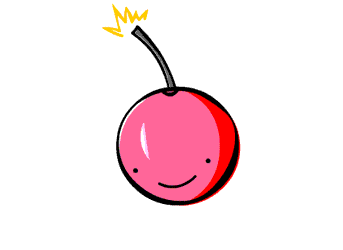Tibalah saat ketika saya harus berhadapan dengan kenyataan : saya pengangguran. Saya tidak lagi melayani. Karena kecewa, hasrat untuk mempelajari Firman lenyap dan saya tidak pernah lagi menyentuh kaset-kaset kotbah. Dan saya terlalu tinggi untuk mencetak surat lamaran kerja.
Seperti cerita-cerita dalam film, bulan demi bulan berganti. Tahun berganti. Dan saya tetaplah remaja manja nan belagu yang gak lagi menyandang gelar pendeta muda. Tumpukan foto saat saya berdiri dengan gagah di mimbar kini hanya berfungsi sebagai pelengkap ingatan, saksi bisu dari kejayaan yang pernah ada. Saya tidak menyadari, sesungguhnya kejayaan itu tidak pernah menjadi milik saya. Semua adalah kepunyaaNya. Ia yang mengangkat, Ia pula yang menurunkan. Namun, karena ambisi dan ego telah membutakan mata batin in, saya menimpakan seluruh kesalahan pada kedua pemimpin saya. Saya menghabiskan waktu untuk mengasihani diri sendiri.
Sampai saat itu tiba. Saya duduk di depan computer, dan teringat pada sesuatu yang telah lama terkubur kiteika saya terlalu sibuk dengan aktivitas keagamaan : saya bias menulis.
Daripada nganggur dan meracuni pikiran dengan hal-hal gak jelas, saya membuka Microsoft Word dan mulai menulis. Awalnya sedikit kaku, namun pelan-pelan menjadi lancer. Saya menulis dan tidak bias berhenti saya menulis apa saja yang tertera di otak, dan dalam sekejap saya saya sudah kerajingan pada computer seperti ‘mencandu’ buku tulis dan pulpen jaman SMP, ketika saya sedang senang-senangnya menuangkan ide yang membeludak di atas kertas (waktu itu jangankan computer, mesin tik aja gak punya).
Waktu terus bergulir. Sang Maestro Kehidupan, dengan caraNya yang ajaib, mulai berurusan dengan saya secara pribadi saat saya menghabiskan belasan jam setiap hadi di depan computer. Saya menjelajah dunia maya dan menemukan banyak pelajaran dan teman baru yang memebuka hati saya terhadap begitu banyak hal. Saya berkenalan dengan banyak orang yang dulu tak pernah saya bayangkan. Saya belajar banyak hal baru. Saya menulis. Dan akhirnya saya paham.
Selama ini, saya mengira saya adalah pengajar yang hebat. Kenyataannya, hidup adalah sebuah universitas, dimana proses belajar terus berlangsung setiap saat—selama hayat masih dikandung badan. Dalam universitas Kehiudpan, saya adalah seorang murid. Saya bukan guru besar, saya hanya salah satu dari sekian banyak orang yang mengikuti mata pelajaran di kelas Kehidupan – sebuah akademi yang tidak pernah meluluskan murid-muridnya.
Saya tercengang. Inilah hiudp yang sebenarnya. Ternyata saya masih harus belajar—sabgat, sangat banyak.
Seorang gadis berbaju kusam dalam bis antarkota yang mengulurkan kepingan uang pada setiap pengamen yang masuk, Itulah pengajar yang sesungguhnya.
Seorang dosen. Yang menyandang gelas S-2 dan meninggalkan karirnya demi mengabadikan hidup di daerah rawan konflik, itulah pengajar yang sesungguhnya.
Seorang kawan yang menghabiskan seluruh uangnya untuk membeli makanan bergizi bagi orangtuanya di desa (sementara ia sendiri hanya memakai sebuah tas kain yang sobek sana-sini), itulah pengajar yang sesungguhnya.
Seorang sahabat yang menyandang predikat Presiden pertama dari Asia dalam sebuah organisasi Internasional yang senyumnya senantiasa tulus tanpa sedikitpun rasa junawa, itulah pengajar yang sesungguhnya.
Seorang nenek tua di dalam angkot dengan sandal jepit dan dompet lusush, itulah pengajar yang sesungguhnya.
Dan mereka, pemimpin yang selama ini saya anggap sebagai ‘duri dalam daging’ karena telah menutup puntiu-pintu kesempatan untuk saya, adalah guru besar yang sejati, karena mereka berani menempuh resiko kehilangan seorang ‘anak’ demi mengajarkan kepada saya sebuah makna penting dalam kehidupan.
Beberapa minggu sebelum menulis artikel ini, sebuah e-mail singgah di inbox saya..
Tahukah kamu,
Aku belajar banyak darimu
Tahukah kamu,
Kau membuka sudut pandang
Baru dimataku
. . . .
just wanna say thanks, karena tulisan kakak vbetul-betul mengubah saya,
jadi lebih baik pastinya.
Mendadak mata saya basah. Terima kasih, Tuhan., karena telah memberi saya kesempatan untuk sekali lagi menyentuh hidup seseorang; untuk berbagai tulisan. Terima kasih atas setiap pelajaran berharga yang saya temukan dimana-mana. Terima kasih untuk kehidupan yang indah dan sangat penuh warna, yang saya jelang setiap harinya.
Terima kasih untuk hati yang masih bias terus bersyukur, hari demi hari, detik demi detik.
Sekarang usia saya 24 tahun, dan saya mencintai setiap jengkalan perjalanan saya. Mencintai kehidupan sampai inci yang terkecil, mengeksplorasi sudut-sudut hidup yang belum terjama, menggemari petualangan, tergila-gila pada hujan deras, aroma tanah basah, kembang api, dan gelembung sabun; kecanduan pada obrolan hangat di sertai candaan-candaan nggak penting, selalu menantikan saat berkumpul dengan sahabat-sahabat tercinta, dan menjadikan menulis sebagai aktivitas yang tak terpisahkan dari kesahariaan saya.
Pemimpin saya (yang sekarang menjadi Bapak dan Ibu Gembala) kini adalah ‘rumah kedua’ saya setelah keluarga. Tempat berpulang yang tak pernah jenuh membagi kehangatan dan menyemai rasa nyaman dihati. Mereka tetap guru besar saya, meski saya sering bandel dan melanggar satu-dua aturan (OK, OK, more than two ^_^_ yang kadarnya agak ‘ringan’ (wink!)
Saya mensyukuri keberadaan mereka seperti saya mensyukuri kehidupan; seperti saya mensyukuri kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya yang tak pernah lelah mereka berikan ketika saya menjelma menjadi anak paling kurang ajar sedunia.
Namun, dari semua pengalaman berharga yang saya lalui bersama pemimpin rohani saya, ada satu momen yang saya syukuri jauh melebihi yang lain : hari ketika mereka menurunkan saya dari mimbar.
Nb: tulisan ini didedikasikan tuk dua orang yang pernah sesak nafas gara-gara kebandelan saya : Steven dan Elly Agustinus.
Terima kasih karena telah bersabar dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi saya, Guru Besar !
Adapted by : G-fresh! (the kingdom: kemana mencari kerajaan Allah ?) 2008
Kesaksian ini sungguh menginspirasi bagi ku, bias nyadari kita smua tuk slalu setia dlm pelayanan tanpa ada perasaan sombong or lbh hebat dr pd yang lainya padahal kita Cuma manusia biasa yang d berikan talenta oleh God, so aku berharap agar kmu2 yg ngebaca artikel ini besa mndptkan berkat yo . . .
Saturday, May 30, 2009
Wednesday, May 27, 2009
arTik3l !!!! part I
GURU BESAR
UNIVERSITAS KEHIDUPAN
Diary Jenny Jusuf
Saya mulai berkotbah pada usia 18 tahun. Seriously. Dan sekedar tambahan info, saya tidak berkotbah di depan anak-anak muda thok. Waktu itu, di bawah naungan sebuah lembaga pelayanan interdenomasi yang di gawangi (halah) sepasang hamba Tuhan muda, saya melayani sebagai pengkotbah keliling. Mulai dari persekutuan kantor, pertemuan pengerja, gereja kecil berlantai semen di desa, sampai gereja besar berinterior mewah yang jemaatnya selalu terlambat setengah jam dari jadwal ibadah (wink-wink).
Yang dikotbahkan? Banyak. Alkitab itu tebal, Jendral, hehehehe. Intinya, ketika masih berusia belasan, saya sudah mencicipi pengalaman yang di miliki hamba-hamba Tuhan berusia puluhan tahun di atas saya.
Rasanya? Nano- nano. Manis-asem-asin. Saya pernah deg-degan juga waktu di minta mendoakan seorang penderita katarak, karena kacamata saya sendiri setebal pantat botol. Saya pernah panas-dingin di atas mimbar karena mendadak lupa nama tokoh Alkitab yang saya kutip untuk berkotbah. Saya pernah nervous saat melangkah kaki ke mimbar . .. dan menemukan Kepala Sekolah saya jaman SMP (yang sangarnya setengah mati!) duduk di bangku terdepan. Namun saya juga merasakan sensasi yang luar biasa ketika berdiri dan menyampaikan firman kepada sekumpulan jemaat.
Di usia semuda itu, dengan masa lalu yang tidak bias di bilang manis, saya merasa bebek jelek dalam diri saya perlahan bertransformasi menjadi angsa cantik. Persis dongeng Hans Christian Andersen. Apalagi ketika ibadah selesai dan pemimpin jemaat melayami saya dengan muka sumringah sambil berpesan, “kapan-kapan melayani di sini lagi, ya.” Dan saya akan mengangguk seraya menjabat si gembala dengan penuh gaya. Tentunya disertai segelintir rasa bangga yang saya tutupi dengan rapat-rapat, karena tidak ada hamba Tuhan yang sombong.
18 tahun. Berkotbah dihadapan jemaat umum. Mendoakan orang. Menyembuhkan orang sakit. Menumpangkan tangan. Mengadakan altar call. Memberikan pesan nubuatan. Apalagi yang belum saya cicipi ?
18 tahun. Sangat muda, sangat dinamis, penuh energi, dan sayangnya, penuh ambisi. Pelan tapi pasti, kesombongan menjalari hati saya seperti ular berbisa.
Saya mulai mengatur sikap dan pembawaan saya sedemikian rupa untuk menimbulkan kesan hamba Tuhan yang sempurna dan tak bercacat cela. Saya mengatur setiap kata yang keluar dari mulut saya. Saya mengatur tindakan-tindakan saya, sampai ke hal yang paling remeh seperti bercanda dan ngobrol santai (!). yang paling parah, saya bahkan mengatur cara saya tertawa.
Sempurnakah saya ? Tentu. Dari luar. Bagi orang-orang terdekat –seperti adik dan para sepupu- saya tak lebih dari figure yang ‘menakutkan’. Saudara-saudara saya tak pernah betah berlama-lama di dekat saya. Kalaupun terpaksa ngumpul bareng, mereka menjaga sikap karena kuatir saya hakimi. Konyolnya, saya sama sekali tidak menyadari perubahan sikap mereka. Saya malah merasa bangga karena mengira telah berhasil memberi contoh teladan bagi saudara-saudara saya (duoooh).
Sudah cukup ? Belum. Yang terburuk dari semuanya adalah, segala hal baik yang saya tampilkan hanya berlaku ketika saya berada diluar rumah. Di rumah, saya adalah saya, seasli-aslinya. Remaja manja yang sombong karena merasa diri paling benar.
Lambat-laun, entah bagaimana caranya, pemimpin saya yang punya naluri lebih tajam dari silet mulai mencium gelagat itu. Saya dipanggil dan dinasehati. Sayangnya, ketika itu terjadi, ego telah menutup Haiti dan menulikan telinga saya dari bisikan nurani. Saya mngiyakan teguran itu, namun tidak kunjung bertobat, malah semakin menjadi-jadi.
Tahap berikutnya, saya memperoleh teguran keras. Saya mengiyakan, dan menganggapnya angina lalu. Namun, tidak seperti badai yang pasti berlalu (halah lagi), teguran keras yang saya abaikan itu tidak ikut berlalu seperti dugaan saya. Pemimpin saya punya insting dan penciuman yang jauh lebih kuat dari harimau lapar.
Tahap berikutnya, saya didisplin. Pelayanan saya dihentikan. Jadwal saya menjadi kosong dalam sekejap.
Merasa di perlakukan tidak adil dan putus asa, saya memutuskan untuk menampilkan sisi asli yang selama ini saya tutupi. I am Who I am.
Hasilnya, saya membuat pemimpin saya menangis. Saya menimbulkan segala jenis kekacauan, mulai dari terang-terangan bersikap membangkang, memeberontak, meremehkan, sampai membanting pintu di depan hidung pemimpin saya ( that’s when she cried)
To be continue . . . .
UNIVERSITAS KEHIDUPAN
Diary Jenny Jusuf
Saya mulai berkotbah pada usia 18 tahun. Seriously. Dan sekedar tambahan info, saya tidak berkotbah di depan anak-anak muda thok. Waktu itu, di bawah naungan sebuah lembaga pelayanan interdenomasi yang di gawangi (halah) sepasang hamba Tuhan muda, saya melayani sebagai pengkotbah keliling. Mulai dari persekutuan kantor, pertemuan pengerja, gereja kecil berlantai semen di desa, sampai gereja besar berinterior mewah yang jemaatnya selalu terlambat setengah jam dari jadwal ibadah (wink-wink).
Yang dikotbahkan? Banyak. Alkitab itu tebal, Jendral, hehehehe. Intinya, ketika masih berusia belasan, saya sudah mencicipi pengalaman yang di miliki hamba-hamba Tuhan berusia puluhan tahun di atas saya.
Rasanya? Nano- nano. Manis-asem-asin. Saya pernah deg-degan juga waktu di minta mendoakan seorang penderita katarak, karena kacamata saya sendiri setebal pantat botol. Saya pernah panas-dingin di atas mimbar karena mendadak lupa nama tokoh Alkitab yang saya kutip untuk berkotbah. Saya pernah nervous saat melangkah kaki ke mimbar . .. dan menemukan Kepala Sekolah saya jaman SMP (yang sangarnya setengah mati!) duduk di bangku terdepan. Namun saya juga merasakan sensasi yang luar biasa ketika berdiri dan menyampaikan firman kepada sekumpulan jemaat.
Di usia semuda itu, dengan masa lalu yang tidak bias di bilang manis, saya merasa bebek jelek dalam diri saya perlahan bertransformasi menjadi angsa cantik. Persis dongeng Hans Christian Andersen. Apalagi ketika ibadah selesai dan pemimpin jemaat melayami saya dengan muka sumringah sambil berpesan, “kapan-kapan melayani di sini lagi, ya.” Dan saya akan mengangguk seraya menjabat si gembala dengan penuh gaya. Tentunya disertai segelintir rasa bangga yang saya tutupi dengan rapat-rapat, karena tidak ada hamba Tuhan yang sombong.
18 tahun. Berkotbah dihadapan jemaat umum. Mendoakan orang. Menyembuhkan orang sakit. Menumpangkan tangan. Mengadakan altar call. Memberikan pesan nubuatan. Apalagi yang belum saya cicipi ?
18 tahun. Sangat muda, sangat dinamis, penuh energi, dan sayangnya, penuh ambisi. Pelan tapi pasti, kesombongan menjalari hati saya seperti ular berbisa.
Saya mulai mengatur sikap dan pembawaan saya sedemikian rupa untuk menimbulkan kesan hamba Tuhan yang sempurna dan tak bercacat cela. Saya mengatur setiap kata yang keluar dari mulut saya. Saya mengatur tindakan-tindakan saya, sampai ke hal yang paling remeh seperti bercanda dan ngobrol santai (!). yang paling parah, saya bahkan mengatur cara saya tertawa.
Sempurnakah saya ? Tentu. Dari luar. Bagi orang-orang terdekat –seperti adik dan para sepupu- saya tak lebih dari figure yang ‘menakutkan’. Saudara-saudara saya tak pernah betah berlama-lama di dekat saya. Kalaupun terpaksa ngumpul bareng, mereka menjaga sikap karena kuatir saya hakimi. Konyolnya, saya sama sekali tidak menyadari perubahan sikap mereka. Saya malah merasa bangga karena mengira telah berhasil memberi contoh teladan bagi saudara-saudara saya (duoooh).
Sudah cukup ? Belum. Yang terburuk dari semuanya adalah, segala hal baik yang saya tampilkan hanya berlaku ketika saya berada diluar rumah. Di rumah, saya adalah saya, seasli-aslinya. Remaja manja yang sombong karena merasa diri paling benar.
Lambat-laun, entah bagaimana caranya, pemimpin saya yang punya naluri lebih tajam dari silet mulai mencium gelagat itu. Saya dipanggil dan dinasehati. Sayangnya, ketika itu terjadi, ego telah menutup Haiti dan menulikan telinga saya dari bisikan nurani. Saya mngiyakan teguran itu, namun tidak kunjung bertobat, malah semakin menjadi-jadi.
Tahap berikutnya, saya memperoleh teguran keras. Saya mengiyakan, dan menganggapnya angina lalu. Namun, tidak seperti badai yang pasti berlalu (halah lagi), teguran keras yang saya abaikan itu tidak ikut berlalu seperti dugaan saya. Pemimpin saya punya insting dan penciuman yang jauh lebih kuat dari harimau lapar.
Tahap berikutnya, saya didisplin. Pelayanan saya dihentikan. Jadwal saya menjadi kosong dalam sekejap.
Merasa di perlakukan tidak adil dan putus asa, saya memutuskan untuk menampilkan sisi asli yang selama ini saya tutupi. I am Who I am.
Hasilnya, saya membuat pemimpin saya menangis. Saya menimbulkan segala jenis kekacauan, mulai dari terang-terangan bersikap membangkang, memeberontak, meremehkan, sampai membanting pintu di depan hidung pemimpin saya ( that’s when she cried)
To be continue . . . .
Subscribe to:
Comments (Atom)